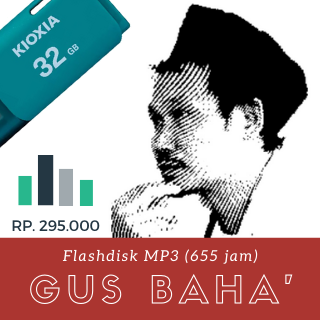|
| NU Online |
Oleh Muhammad Afiq Zahara
Dalam antologi puisi panjangnya, In The Mecca, Gwendolyn Brooks (1917-2000 M) mengatakan: “One
reason that cats are happier than people is that they have no
newspapers—satu alasan kenapa kucing lebih bahagia dari manusia adalah,
bahwa mereka tidak memiliki koran (sekarang, media online).”
Ya,
kucing hidup tanpa perlu mengkhawatirkan fitnah dan hoaks. Mereka tidak
perlu memahami besarnya pengaruh fitnah dan hoaks atas pribadi
seseorang dan lingkungan tertentu; mereka tidak perlu memahami kejamnya
pembunuhan karakter dan ujaran kebencian. Asal perut kenyang, mereka
bahagia. Sederhana saja.
Sekarang ini hoaks
telah dibudidayakan seperti hewan ternak, tersebar dimana-mana dan
disebarkan oleh siapa saja. Daya kritis manusia dalam memahami berita
seakan mati rasa. Apapun yang dibaca, jika sesuai dengan selera, dimakan
mentah-mentah dan dipercaya. Jika tidak sesuai dengan selera, langsung
divonis sebagai berita bohong.
Ini masalah serius. Melihat berita dengan ‘selera’ telah menghalangi terciptanya kultur tabayyun
(konfirmasi informasi) di masyarakat kita. Pemilahan berita tidak
berdasarkan fakta jurnalistik. Selama berita itu sesuai dengan ‘selera’,
kita akan menyebarkannya kemana-mana, melalui media sosial (medsos)
yang telah hampir dipakai seluruh penduduk Indonesia.Lalu, bagaimana
agama menyikapi hal ini?
Sikap agama jelas,
tidak ada ruang untuk kebohongan (hoaks) dalam agama. Anehnya, ada orang
yang mengatakan, penyebaran hoaks adalah bentuk kepasrahan kepada
Allah, dalam arti berjuang di jalanNya. Ada pula yang menganggap wajar
penambahan sebuah berita, apalagi jika berhubungan dengan agama. Ini
adalah hal yang benar-benar aneh.
Dalam tradisi Islam, terdapat disiplin ilmu musthalah al-hadîts.
Saya tidak akan membicarakan panjang lebarilmu tersebut. Saya hanya
ingin mengatakan, dalam memahami berita umat Islam seharusnya mengacu
pada ilmu tersebut. Tidak mudah mengambil kesimpulan dan harus melakukan
kroscek kritis dari mulai sumber berita, siapa yang memberitakannya
sampai proses pengikisan penambahan berita bohong yang menyertainya.
Imam al-Syâfi’i dalam al-Risâlah menyebutnya sebagai al-kadzib al-khafi (kebohongan yang halus), yaitu “dzalika al-hadîts ‘an man lâ yu’rafu sidquhu—menyebarkan hadits dari orang yang tidak diketahui kejujurannya.” (Muhammad bin Idrîs al-Syâfi’i, al-Risâlah, hlm 401).
Artinya,
sebelum benar-benar mengetahui kejujuran orang yang memberitakannya
secara langsung dan meneliti secara kritis sumber berita tersebut, kita
sebaiknya menahan diri untuk menyebarkannya. Jika berita itu benar, kita
tidak mendapatkan dosa. Jika berita itu bohong, kita telah turut serta
dalam menyebarkan fitnah.
Di era berkemajuan
ini, media telah membawa zaman ke arah ‘mediakrasi’, sehingga propaganda
disebut pengetahuan dan gosip disebut berita. Setiap hari kita disuguhi
berita-berita semacam itu. Efeknya, cara pandang kita terhadap dunia
perlahan-lahan bergeser, dari justifikasi logis-kritis menjadi
justifikasi propagandis, meski bisa dikatakan tidak semua orang termakan
oleh hal itu.
Bagaimana dengan penyebaran
berita hoaks sebagai bentuk syiar agama? Jawabannya sama, ketika
berkaitan dengan fitnah (pembunuhan karakter) agama tidak memberikan
ruang, dengan alasan apapun, “al-fitnah asyaddu min al-qatl—fitnah lebih jahat dari pembunuhan.”
Bahkan,
jika kita perluas kajiannya, Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika
diajak kaumnya untuk menyembah berhala, Ia mengatakan(Q.S. al-Shaffat
[37]: 89): “fa qâla innî saqîm—sesungguhnya
aku sakit. ”Kebohongan itu menjadi penghalang dirinya memberi syafaat
di hari akhir. Ketika sekumpulan orang mendatanginya untuk meminta
syafaat, Ia menjawab:
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات
“Sungguh
Tuhanku, hari ini, telah murka (kepadaku) dengan kemurkaan yang belum
ada misal sebelumnya, sesungguhnya aku telah berdusta tiga kali...” (H.R. Imam Bukhari).
Perbedaannya
adalah, tidak ada unsur fitnah ataupun pembunuhan karakter dalam
kebohongan Nabi Ibrahim. Tidak ada pribadi yang dirugikan. Meski
demikian, Allah tetap menganggapnya sebagai dusta, sehingga Nabi Ibrahim
tidak memiliki hak memberi syafaat kepada umatnya, seperti Kanjeng Nabi
Muhammad Saw. Manusia pilihan yang tidak pernah berbohong sekalipun.
Lah
kita, tidak memiliki kemaksuman seperti Nabi Ibrahim, tidak memiliki
amal ibadah seperti Nabi Ibrahim. Tanpa pertimbangan yang matang, dengan
berani menyebarkan berita bohong atau membuatnya. Andai amal Nabi
Ibrahim adalah gunung, satu kerikilnya saja masih terlalu besar untuk
dibandingkan dengan amal yang kita kumpulkan sampai mati.
Kita harus berhati-hati dalam membaca berita. Lakukan critical analysis (al-tahlîl al-naqdlî, analisa kritis), penyelusuran sumber (takhrîj
dan kritik sanad) dan evaluasi konten berita (kritik matan). Jangan
dimakan mentah-mentah dan disebarkan begitu saja. Pembacaan kritis ini
sangat diperlukan agar terhindar dari budidaya fitnah dalam bentuk
berita. Sebaik-baik berita yang kita baca, lebih baik berita yang kita
dengar dan lihat secara langsung, sami’nâ wa atha’nâ.
Saya menutupnya dengan perkataan Mark Twain (1835-1910): “If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed—jika
kau tidak membaca koran (sekarang media online), kau kurang informasi.
Jika kau membacanya, kau mendapatkan informasi yang salah. ”Semoga kita
bisa menghindarinya. Wallahu a’lam. [dutaislam.com/pin]
Penulis
adalah Alumnus Pondok Pesantren al-Islah, Kaliketing, Doro, Pekalongan
dan Pondok Pesantren Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen.
Sumber: NU Online
Baca: Cara Cek Berita Hoax