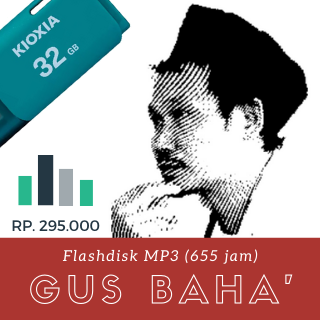|
| Takwil adalah mengalihkan makna ayat Al-Quran yang rajih kepada yang marjuh dengan adanya qarinah. |
Oleh Siti Nadiratul K.
Dutaislam.com - Al-Qur’an adalah rujukan syari’at Islam yang bersifat menyuluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari’at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rincianya.
Sebagai kitab suci yang di turunkan oleh Allah Swt. dengan lafadz dan sekaligus maknanya, ia diturunkan dalam bahasa Arab. Meskipun sebagian kecil kata-katanya tidak berasal dari bahasa arab, tapi sudah dimasukkan dalam bahasa Arab. Karena itu ulama ushul fiqih telah berupaya dengan mengikuti lebih dalam tentang lafadz yang ada di Al-Qur’an dengan meneliti klasifikasi lafadz dan berbagai problematika pentakwilan maknanya.
Ta’wil sendiri adalah mengalihkan lafadz dari makna zhahirnya (makna rajih) kepada makna esoteris (makna marjuh) berdasarkan dalil (qarinah). Para ulama menjadikan adanya dalil sebagai syarat utama dalam melakukan ta’wil. Adanya dalil shahih yang menguatkan merupakan ciri ta’wil yang shahih, sedangkan tanpa dalil adalah ta’wil yang batil dan mengikuti hawa nafsu.
Menurut para ulama, ada bentuk dalil-dalil yang digunakan untuk merajihkan makna esoteris (makna marjuh) dari pada makna zhahir. Takwil tidak dapat dilakukan pada lafazh yang khafi (samar), karena meskipun tersembunyi tapi maknanya jelas.
Begitu juga pada lafazh musytarak, meskipun memiliki banyak makna, namun maknanya dapat diketahui dengan adanya indikasi (qarinah) di luar lafadz, dan bukan mengalihkan lafadz dari maknanya yang kuat (rajih) kepada yang lemah (marjuh), bukan dengan pendekatan ushul fiqh tapi pendekatan bahasa:
- Nash Al-Qur’an dan As-Sunnah; seperti firman Allah tentang keharaman bangkai (hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah dalam QS. Al-Maidah: 3). Ayat ini menerangkan keharaman segala sesuatu dari bangkai, termasuk kulitnya. Namun ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat tentang kambing milik Maimunah Radhiyallah ‘anha yang mati dan akan dibuang, “Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya kemudian kalian samak dan manfaatkan?”. Para sahabat menjawab, “Tapi ini bangkai?”. Beliau menjawab, “Yang diharamkan dari bangkai hanyalah memakannya”. Dalil dari hadits ini mengalihkan sebuah lafadz dari makna zhahirnya.
- Ijma’; seperti firman Allah dalam QS. al-Jumu’ah: 9, secara zhahir ayat ini berlaku kepada semua orang beriman baik laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, budak, maupun anak-anak. Tetapi ijma’ mengecualikan anak-anak yang belum baligh.
- Qiyas; di antara para ulama, ada yang mensyaratkan harus dengan qiyas jaliy, seperti qiyas budak laki-laki pada budak perempuan dalam hal pembebasannya. Sedangkan qiyas fariq tidak berlaku.
- Hikmah Tasyri’ dan kaidah-kaidah dasar syari’at; seperti kewajiban zakat dari empat puluh ekor kambing dengan satu ekor. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . Menurut ulama Syafi’iyah, membayar dengan seekor kambing sesuai dengan zhahir lafadz hadits dan tidak boleh menggantinya dengan uang (ikhraj al-qiymah) karena lafazznya jelas, khusus, dan qath’i. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, boleh menggantinya dengan uang (ikhraj al-qiymah) karena hikmah dari mengeluarkan zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang faqir dan uang lebih bermanfaat untuk mencukupi segala kebutuhan mereka serta lebih sesuai dengan keinginan syari’at.
Dalam kaitannya dengan masalah makna, seorang mujtahid ketika akan mengalihkan lafadz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Makna lughawi bahasa Arab, seperti kata shalat yang berarti doa, zakat yang berarti penyucian, dan shaum yang berarti menahan.
- Istilah-istilah syar’i; kata yang memiliki pengertian khusus dalam syar’i, sehingga makna kata tersebut harus dikembalikan kepada makna syar’i, bukan kepada makna lughawi (bahasa).
- Istilah dalam urf (kebiasaan), baik urf yang bersifat umum seperti kata الدابة untuk makhluk yang berkaki empat (melata) atau kata الغائط untuk kotoran, maupun urf yang bersifat khusus seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu, fiqh, hadith, dan ilmu-ilmu lainnya.
Selain memperhatikan tiga hal di atas, dalam mengalihkan lafazh dari makna yang kuat kepada makna yang lemah juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat atau berdasarkan dalil. Dalam hal ini, ada tiga macam pengalihan lafazh dari makna zhahirnya:
- Mengalihkan kepada yang terdekat. Seperti lafazh إذا قمتم إلى الصلاة dalam QS. Al-Maidah: 6, kata القيام dalam ayat ini dita’wilkan (diartikan) ketika hendak dan ingin melaksanakan shalat.
- Mengalihkan kepada yang jauh. Hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil shahih yang menguatkan bahwa yang dimaksud dari lafadz tersebut adalah makna yang jauh. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Ghailan Ath-Thaqafi ketika masuk Islam dan masih memiliki sepuluh orang istri, ” أمسك أربعًا و فارق سائرهن (Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah sisanya). Ulama Hanafiah menta’wilkan hadits ini dengan perintah untuk menikahi empat orang wanita tersebut dengan akad baru karena mereka membedakan pernikahan kafir dan Islam. Pendapat ini ditentang oleh ulama lain yang berpendapat bahwa tidak perlu mengulangi akad nikahnya dengan alasan Ghailan masih baru masuk Islam dan belum mengetahui hukum-hukum Islam, dan seandainya pendapat pertama benar, niscaya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam akan menjelaskan hal itu kepada Ghailan.
- Ta’wil batil yaitu mengalihkan kepada makna yang tidak terkandung dalam lafadz. Seperti ta’wil yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah terhadap firman Allah أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (…atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...). Mereka menta’wilkan lafadz ini dengan selain kabilah kalian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam.
Syarat-Syarat Mentakwilkan
Para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah ta’wil sebagai berikut:
- Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada ta’wil. Seperti antara QS. An-Nisa ayat 2 dan 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim (mutlak), yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka, kata yatim pada ayat pertama harus dita’wil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi.
- Ta’wil tidak boleh menggugurkan nash syar’i lainnya, karena ta’wil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zhanni sedangkan nash yang bersifat zhanni tidak bisa mengalahkan nash yang bersifat qath’iy. Seperti QS. Al-Maidah: 6 ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) kemudian dibaca kasrah (أَرْجُلِكُمْ) oleh kalangan Syi’ah, mereka memilih kasrah bukan fathah dengan alasan athaf. Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya (cukupnya) mengusap kaki dalam wudlu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal; pertama, menggugurkan hadits-hadits shahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. Kedua, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki. Sehingga pembatasan (qaid) pada mata kaki menjadi tidak berguna. Padahal kerancuan makna dalam kalamullah mustahil terjadi.
- Lafadz yang ingin dita’wil adalah lafadz ambigu dan bisa dita’wil. Menurut kalangan Hanafiyah, lafazh yang ingin dita’wil harus lafadz nash dan zhahir. Misalkan lafazhnya adalah lafadz umum yang dapat dikhususkan (ditakhshish), atau lafazh mutlak yang dapat diberi batasan (taqyid), atau lafadz bermakna hakiki yang dapat diartikan secara metaforis (majazi), dan sebagainya. Maka, jika ta’wil dilakukan pada nash khusus (bukan nash umum), tidak diterima.
- Ta’wil (mengalihkan lafazh dari makna zhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna zhahir. Misalkan mengkhususkan nash umum berdasarkan dalil pengkhusus (takhshish), atau memberikan batasan (taqyid) pada nash mutlak berdasarkan dalil yang memberikan batasan (mentaqyid). Maka, ta’wil yang tanpa dalil, atau dengan dalil tapi dalilnya lemah (marjuh), atau sederajat kekuatannya (musawi) dengan lafadz yang dita’wil, tidak diterima.
- Orang yang hendak melakukan ta’wil, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar’i. Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukannya karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu.
- Ta’wil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar’i, atau makna urf (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil quru` (QS. Al-Baqarah: 228) dengan arti haid atau suci adalah ta’wil sahih, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk quru'. Ta’wil yang tidak sesuai makna bahasa, syar’i, atau urf, tidak diterima.
- Jika ta’wil dengan qiyas, maka hendaknya menggunakan qiyas jaliy menurut ulama Syafi’iyah. Bagi mereka, dalam qiyas jaliy telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan (i’tibar al-fariq) antara far’ dan ashl, seperti qiyas antara hamba sahaya laki-laki (al-‘abd) dengan hamba sahaya perempuan (al-amah) dalam hukum perbudakan. Sedangkan qiyas khafiy, masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan (i’tibar al-fariq) antara far’ dan ashl, seperti qiyas antara anggur dengan khamr ketika diminum dalam jumlah.
Selain menetapkan aturan dalam menta’wil , para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan bagi orang yang ingin melakukan ta’wil terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dengan kriteria yang cukup ketat, yang juga merupakan kriteria bagi seorang mujtahid dan mufassir:
- Memiliki ilmu tentang Al-Qur’an. Yakni mengetahui dan menguasai ayat-ayat Al-Qur’an terutama ayat-ayat hukum dan tidak disyaratkan harus menghafalnya.
- Memiliki ilmu tentang As-Sunnah, yakni mengetahui dan menguasai hadits-hadits hukum dan mampu menyebutkanya, serta membedakanya mana yang shahih dan mana yang dhaif, mengetahui ijma' dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.
- Menguasai ilmu ushul fiqh sebagai modal ijtihad.
- Menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengetahui makna-makna dari setiap katanya, karena ta’wil-ta’wil batil. Kebanyakan orang ajam tidak menguasai bahasa Arab dan mengetahui maqashid syari’ah dengan baik.
Macam-Macam Syarat Menakwilkan
Lafaz yang ditakwil, harus betul-betul memenuhi kriteria dan masuk dalam kajiannya. Dalil-dalil yang telah ditafsirkan dan ditetapkan ketentuan hukumnya tidak bisa ditakwil. Namun menurut Hanafiyah, takwil itu boleh sekalipun pada nash yang zhahir dan semua dalil yang berhubungan dengan syariat Islam.
- Takwil itu harus berdasarkan dalil sahih yang bisa menguatkan takwil. Misalnya, dengan mentakhsis yang amm. Dan takwil macam inilah yang paling banyak dilakukan.
- Lafadz menekan arti yang dihasilkan melalui takwil menurut bahasa. Misalnya, mentaqyid yang mutlaq dengan muqayyad. Ketila sunnah mentaqyid wasiat yang ada dalam Al-Qur’an dengan sepertiga.
- Takwil tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath’i, karena nash tersebut bagian dari aturan syara’ yang umum.
Takwil adalah metode ijtihad yang bersifat zhanni, sedangkan zhanni tidak akan kuat melawan yang qath’i. Contohnya menakwilkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur’an dengan mengubah arti yang zahir menjadi fiksi (yang tidak terjadi). Penakwilan seperti itu bertentangan dengan kejelasan ayat yang qath’i yang menjadikan kisah tersebut sebagai kejadian sejarah yang nyata.
Arti dari penakwilan nash harus lebih kuat dari zahir, yakni dikuatkan dengan dalil sebagai acuan dalam menentukan kekuatannya adalah sejauh mana kejelasan maksud syara’ dalam setiap dilalahnya.
Takwil itu terkadang tidak membutuhkan dalil, tetapi dimungkinkan berdasarkan pada pemahaman yang dangkal, akal dan teks sesuatu. Takwil seperti itu dinamakan oleh ulama Ushul dengan istilah takwil qarib yang cukup memakai dalil yang terendah.
Misalnya firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 6. Arti zahir dari ayat, yakni "…apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku…" adalah mengharuskan berwudlu setelah melaksanakan shalat.
Pemahaman seperti itu tentu saja bertentangan dengan syarat sahnya shalat yang mengharuskan berwudlu terlebih dahulu. Dan syarat itu harus didahulukan, baik menurut akal ataupun syara’ agar shalatnya sah.
Untuk itu, lafaz al-qiyamu dalam firman Allah ta’ala di atas harus ditakwilkan. Kemudian diubah dari artinya yang hakiki kepada artinya yang majazi yaitu al-‘ajmu (bermaksud) mendirikan, bukan mendirikan dengan sendirinya. Dengan demikian, arti ayat tersebut akan menjadi sah dengan kalimat:
اذا عزمتم او اذا ارد تم
Itulah beberapa persyaratan takwil. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, dinamakan takwil ba'id.
Jika ada penyimpangan dari persyaratan tadi, maka takwil seperti itu tertolak dan masuk kategori takwil batil.
Namun, para ulama berbeda pendapat tentang keberadaan takwil ba’id tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam penetapannya. Ada yang berpendapat bahwa sebagian takwil itu ba’id, tetapi sebagian lagi menilai bahwa takwil seperti itu dikatakan qarib dan sahih.
Misalnya tentang kifarat khuntsa (banci) ketika melanggar sumpah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa: "…maka kifarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin…".
Zahir nash menyatakan harus memberi makan dalam jumlah yang khusus, yaitu sepuluh orang miskin. Karena ‘adad adalah lafadz khusus yang mengindahkan pada qath’i secara ijma’. Baca: Pengertian Illat, Sebab dan Hikmah dalam Qiyas Ushul Fiqih (Download PDF).
Namun golongan Hanafi menakwilkan lafaz ‘asyarah pada arti yang tidak tercakup di dalam kata tersebut, yakni sepuluh makanan atau ukuran sepuluh makanan bagi orang-orang miskin. Menurut pendapat mereka, lafadz ‘asyarah itu bukan dikhususkan kepada jumlah (fakir), namun merupakan ukuran yang wajib (dikeluarkan) dari makanan untuk sepuluh orang miskin.
Dengan penakwilan seperti itu, menurut Abu Hanifah, kita dibolehkan untuk memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin atau kepada satu orang miskin dengan sepuluh makanan, karena ukuran itu satu untuk dua keadaan. Menurut mereka, takwil seperti itu didasarkan pada maksud kebutuhan mendesak yang merupakan hikmah disyari’atkannya nash.
Namun, penakwilan di atas dianggap takwil ba’id dan dinyatakan batil oleh Imam Syafi’i, karena lafadz ‘asyarah adalah lafaz khusus yang menunjukkan arti qath’i, sehingga tidak membutuhkan penakwilan.
Dan hikmah syari’atnya bukanlah seperti pendapat mereka, tetapi pembagian ukuran harta yang wajib dikeluarkan sesuai jumlahnya, supaya manfaatnya dirasakan umum. Selain itu, penakwilan mereka juga membutuhkan idhafat kalimat sebagai tambahan nash, sehingga ayat tersebut menjadi
اطعام طعا م عشر ة مسا كين
Sebagi batasan wajib, padahal idhafat seperti itu menyalahi ashal. Jadi, kecacatan takwil di atas disebabkan dua perkara:
- Meremehkan ‘adad, lafadz khusus yang jelas menunjukkan arti yang qath’i maka haruslah menjaga arti yang qath’i tersebut dan tidak meremehkannya.
- Penambahan kalimat terhadap nash adalah menyalahi ashal. Jelaslah bahwa penakwilan seperti itu dinamakan takwil ba’id karena keluar dari persyaratan takwil yang sah.
Etika Pentakwilan
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ta’wil harus berdasarkan dengan dalil (qarinah) yang kuat, karena merupakan syarat utama sebagai ta’wil yang shahih. Jika tidak berdasarkan pada dalil yang shahih maka ta’wil tersebut adalah ta’wil batil dan mengikuti hawa nafsu.
Selain itu, sebelum melakukan ta’wil seorang muawwil juga harus memperhatikan makna zhahir lafadz terlebih dahulu atau tafsir terlebih dahulu. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Az-Zarkasyi bahwa “Lâ mathmaha fi al-wushul ila al-bâthin qabla ihkâm al-zhâhir”, tidak ada harapan sampai kepada makna batin teks sebelum meraih makna zhahirnya.
Ditambah pula dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama, yang telah kami paparkan diawal tulisan.
Kesalahan Pentakwilan
Ta’wil memiliki tiga macam; pertama, ta’wil yang dekat seperti lafadz idza kuntum ila ash-shalah yang dita’wilkan dengan ketika hendak melaksanakan shalat. Kedua, ta’wil yang jauh seperti hadits Ghailan Ath-Thaqafi yang dita’wilkan oleh ulama Hanafiyah dengan perintah untuk menikahi empat orang wanita tersebut dengan akad baru karena mereka membedakan pernikahan kafir dan Islam.
Ketiga, ta’wil batil yaitu mengalihkan kepada makna yang tidak terkandung dalam lafadz. Misalnya, pendapat Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar yang menakwilkan hakikat malaikat ialah kecenderungan kebajikan dan kejahatan dalam jiwa manusia.
Berdasarkan syarat-syarat takwil di atas, kita akan dapat menilai sahih tidaknya suatu takwil. Jika suatu ayat tidak memenuhi syarat-syarat takwil tersebut, maka takwil yang dihasilkan adalah tidak sahih alias batil. Adapun bagi orang-orang yang telah melakukan penakwilan yang salah, semoga Allah memaafkan kesalahan mereka, dan mengagungkan mereka dengan ilmu dan ijtihad yang mereka lakukan.
Kesimpulan
Ta’wil sendiri adalah mengalihkan lafazh dari makna zhahirnya (makna rajih) kepada makna esoteris (makna marjuh) berdasarkan dalil (qarinah). Para ulama menjadikan adanya dalil sebagai syarat utama dalam melakukan ta’wil. Adanya dalil shahih yang menguatkan merupakan ciri ta’wil yang shahih, sedangkan tanpa dalil adalah ta’wil yang batil dan mengikuti hawa nafsu.
Makna yang lemah harus memperhatikan; makna lughawi, makna istilah-istilah syar’i, dan makna istilah dalam urf tertentu seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu, fiqh, hadith, dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap lafadz harus dikembalikan maknanya kepada tiga macam makna tersebut sesuai dengan qarinah lafadznya.
Jika menunjukkan kepada makna lughawi maka harus dikembalikan kepada makna lughawi. Jika menunjukkan kepada makna syar’i maka harus dikembalikan kepada makna syar’i, dan jika menunjukkan kepada makna urf maka harus dikembalikan kepada makna urf. Terkadang dalam ketiga makna tersebut masih memiliki bagian, seperti makna syar’i terkadang terbagi menjadi hakiki dan majazi.
Dalam masalah ta’wil, para ulama ushul merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Qur’an untuk kepentingan istimbath al-ahkam. Sehingga kajian para ulama ushul merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadits. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk ta’wil, di antaranya mengkhususkan lafadz yang bersifat umum (takhshish al-umum), membatasi lafazh yang mutlak (taqyid al-muthlaq), mengalihkan lafazh dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, atau dari makanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah.
Para ulama ushul juga yang membuat kaidah-kaidah ta’wil di antaranya; orang yang melakukan ta’wil harus memiliki kriteria seorang mujtahid, harus berdasarkan pada dalil yang shahih, dan tidak bertentangan dengan nash yang lain.
Kaidah-kaidah ta’wil yang dibuat oleh para ulama dan konsep pengalihan makna dalam ta’wil ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara ta’wil dan hermeneutika. Dalam hermeneutika, seseorang tidak terikat dengan makna istilah-istilah syar’i, tidak perlu menggunakan dalil-dalil syar’i, tidak memperhatikan apakah hasil penafsiran tersebut sesuai dengan nash-nash syar’i yang lain atau bertentangan, dan tidak memperhatikan orang yang melakukannya apakah memiliki kemampuan atau tidak.
Dengan demikian, hasil penafsiran dalam hermeneutika menjadi bias dan relatif tergantung kepada orang yang melakukan penafsiran. Hermeneutika menjadikan agama sebagai kumpulan interpretasi, dan tidak ada klasifikasi teks, sehingga menurut para hermeneut, tidak ada teks yang tidak dapat ditafsirkan. [dutaislam.com/ab]
[Download PDF]
Siti Nadiratul K, mahasiswi UIN Walisongo Semarang.
Artikel disampaikan di hadapan dosen pengampu, Mishbah Khoiruddin Zuhri, M.A