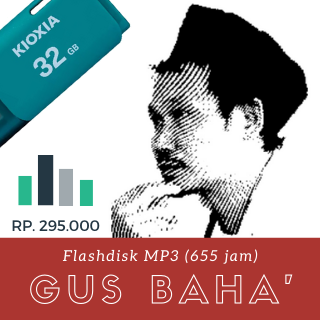|
| Ijma sukuti (makalah ushulul fiqh) |
DutaIslam.Com - Ijma’ dapat dicapai dengan pengungkapan lisan, tindakan atau secara diam-diam. Masalah ini telah dikupas pada pembahasan rukun ijma’. Ijma’ secara teknis disebut ‘azimah (reguler), dan yang secara diam-diam disebut rukhshah (konsesi). Rukun ijma’ dan pembagiannya atau ‘azimah dan rukhshoh tidak dapat ditemukan sebelum abad ke-5 hijriyah.
Para mujtahid yang melakukan sidang ijma’ tidak selalu mendapat jalan yang mulus untuk mendapatkan persetujuan semua kalangan. Akan tetapi ada golongan mujtahid yang menyepakati ijma’ dalam aksi diam di antara mereka. Bagaimana bisa orang yang diam dikatakan sepakat? Inilah yang akan kita bahas, yakni: ijma’ secara diam-diam atau yang dikenal dengan nama ijma’ sukuti. Baca: Kedudukan Ijma' dalam Hukum Islam Menurut Madzhab Ibnu Hazm (PDF).
Pengertian ijma’ sukuti
Pembahasan mengenai rukun-rukun ijma’, jenis-jenisnya dan kemungkinan terjadinya sidang sudah dibahas sebelumnya. (Baca: Rukun Ijma dan Syarat-Syaratnya). Di antara semua itu, ada suatu pertanyaan yang timbul, bagaimana dengan keabsahan ijma’ sukuti? Ijma’ yang dilakukan dengan diam oleh para ulama itu.
Ijma’ sukuti adalah ijma’ yang sebagian dari mujtahid (pada suatu masa) mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka (sebagian yang lain) tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau bahkan menentang pendapat itu. Ijma’ sukuti ini mempunyai kualitas hukum dzanni.
Lebih jelasnya, jika pendapat dari beberapa ulama mengenai suatu masalah yang diperselisihkan tersebar luas di kalangan masyarakat, dan para ahli selebihnya menerimanya melalui lisan atau dengan berdiam diri, maka boleh dikatakan bahwa kesepakatan telah dicapai dalam masalah tersebut. Dan jenis ijma’ jenis ini dikenal sebagai rukhshah (kelonggaran) atau ijma’ sukuti (kesepakatan diam-diam)
Al-Bazdawi berkeyakinan bahwa ijma’ diam-diam itu sah asalkan memenuhi dua syarat, yaitu :
- Bahwa pendapat dari satu ulama atau sekelompok ulama harus diketahui oleh seluruh ulama’.
- Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan masalah yang diperselisihkan itu harus sudah lewat.
Dalam penjelasan 'azimah dan rukhshah, al-Bukhori mengatakan bahwa,
- Yang pertama, menunjukkan proses terhadap ijma’, sebab kata ‘azimah mengandung konotasi keteraturan atau keaslian (ashl).
- Yang kedua, mengimplikasikan ijma’ yang dicapai karena terdesak kebutuhan (dharurat). Sebab rukhsah didasarkan atas kebutuhan.
Ijma’ dengan berdiam diri dinamakan rukhsah agar ketidakmampuan dan ketidak-salehan tidak selalu dinisbatkan kepada para ahli hukum yang berdiam diri dalam permasalahan yang memerlukan penyuaraan pendapat mereka. Seseorang yang berdiam diri dalam masalah di mana dia harus berbicara disebut pula dengan syaithan bisu.
Para pendukung Ijma’ Sukuti
Mayoritas ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H/780-855 M) mengatakan bahwa kesepakatan seperti itu termasuk ijma’, dan bisa dijaikan hujjah yang qoth’i (pasti). Pendapat lain dikemukakan oleh Abu ‘Ali al-Jubba’i (tokoh Mu’tazilah) yang menyatakan bahwa kesepakatan seperti itu termasuk ijma’ dengan syarat; generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut telah habis, karena apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut telah habis, sementara mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai akhir hayat mereka, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.
Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, kehujjahan ijma’ sukuti hanya menggunakan logika/dalil akal. Dalil akal yang mereka kemukakan menyatakan bahwa ijma’ shorih harus disepakati oleh setiap mujtahid yang hidup pada masa terjadinya ijma’, dan masing-masing mereka mengemukakan pendapat mereka, serta menyutujui hukum yang ditetapkan.
Hal ni tidak mungkin terjadi karena biasanya ijma’ yang dikemukakan ulama tesebut berawal dari pendaapat seorang atau sekelompok mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya diam. Di samping itu, para ulama sepakat mengatakan bahwa ijma’ sukuti bisa dijadikan hujjah dalam masalah keyakinan.
Berikut ulasan pendapat ulama Hanabilah dan Hanafiyah:
1). Adalah kewajiban para ulama untuk mempelajari hasil ijtihad dari ulama lain, yang diungkapkan di zaman mereka. Apabila seorang ulama’ mengemukakan dan menyebarluaskan hasil ijtihadnya dalam suatu kasus, sementara ulama lain (setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad itu), diam saja, maka hl itu menunjukkan persetujuannya. Karena ulama’ ushul fiqh sepakat menyatakan:
السكوت في مضع البيان بيان
Artinya:“Diam saja ketika suatu penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan.”
Maksudnya sikap diam para ulama dianggap sebagai penjelasan atas persetujuan mereka terhadap suatu ijtihad yang telah diungkapkan.
2). Tidak dapat diterima (tidak layak) jika para ahli fatwa diam saja ketika mendengar adanya fatwa ulama lain. Karena (sesuai dengan kebiassaan dikalangan ulma’ fatwa), jika ada seorang ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu kasus kejadian, maka para ulama lain harus menanggapinya jika fatwa itu dianggap tidak benar. Karenanya, apabila para ulama itu diam saja, maka sikap tersebut dianggap sebagai pertanda setuju.
Di samping itu, apabila para ulama lain (yang tidak mengeluarkan fatwa hukum) menganggap fatwa itu menyimpang dari nash, atau metode yang digunakan tidak sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama, lalu mereka diam saja, maka mereka berdosa. Sudah merupakan kewajiban bagi mereka untuk mempelajari, menganalisis dan membantah suatu fatwa bila ternyata tidak sejalan dengan nash atau tidak sejalan dengan metode yang ada.
Jumhur ulama’ yang menolak kehujjahan ijma’ sukuti mengatakan bahwa rukun dan syarat ijma’ itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang hidup di zaman terjadinya ijma’ tersebut. Dan masing-masing mereka terlibat membicarakan hukum yang akan ditetapkan itu.
Sedangkan ijma’ sukuti merupakan pendapat pribadi yang disebarluaskan, sedangkan mujtahid lainnya diam saja. Diamnya mujtahid tidak bisa ditafsirkan sebagai tanda persetujuan mereka, karena diamnya mereka mungkin disebabkan kondisi pribadi dan kondisi di lingkungan yang mereka hadapi.
Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, posisi ijtihad yang dilakukan seorang ataupun sekelompok mujahid itu tidak lebih dari ijtihad yang sifatnya dzanni (relatif) sehingga tidak wajib diikuti mujtahid lain, dan karena itu pula tidak dinamakan ijma’.
Beberapa pandangan tokoh pendukung dan alasan mereka:
Al-Sarakhsi
Al-Sarakhsi menyatakan bahwa Allah tidak bermaksud mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Dalam praktik adalah mustahil untuk mendengar secara langsung pendapat para ulama dimasa lampau, atau pendapat tiap-tiap dan seluruh ulama dalam setiap generasi. Penyebaran suatu pendapat individual seorang ulama mengenai suatu masalah yang sedang diperselisihkan di kalangan masyarakat, dan sikap diam dari ulama-ulama selebihnya menanggapi pendapat tersebut, akan dianggap cukup untuk mengesahkan ijma’. Ini disebabkan karena tidaklah halal bagi para ulama untuk berdiam diri jika mereka tidak setuju dengan pendapat yang telah disepakati oleh masyarakat. Ini juga menghapus kemungkinan ketidaksetujuan mereka jika mereka tetap diam, dan sebaliknya kemungkinan persetujuan mereka akan lebih disukai.
Abul Husayn al-Bashri
Abul Husayn al-Bashri mengatakan, jika pendapat dari seorang ulama tersebar luas di masyarakat dan para ulama lainnya berdiam diri dan tidak menyuarakan ketidaksepakatan mereka, maka ijma’ telah tercapai, asalkan telah diketahui bahwa mereka benar-benar sepakat. Jika kesepakatan mereka tidak diketahui, maka akan dilihat apakah masalah yang sedang diperselisihkan itu menyangkut penafsiran hukum (ijtihadi) atau tidak. Jika tidak, maka akan dilihat lagi apakah masalah itu berhubungan dengan kewajiban hukum (taklif) atau tidak. Jika tidak, maka pendapat yang disebarluaskan itu mungkin salah, karena para ulama lainnya tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan masalah-masalah semacam itu.
Mereka sangat mungkin telah bermaksud untuk mengabaikan masalah yang tidak cukup berharga untuk dipertimbangkan, dan kesepakatan mereka mungkin telah mencakup kenyataan ini. Apabila masalah yang bersangkutan tidak melibatkan kewajiban hukum, dan para ulama lainnya tidak menyuarakan ketidaksetujuannya, maka ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut benar. Para ahli hukum berkewajiban untuk menolak atau menyuarakan pandangan mereka jika pendapat tersebut salah.
Dan jika pendapat tersebut benar, kebalikannya pasti salah, karena ini adalah masalah di mana kebenaran terletak pada salah satu pendapat. Jika masalah tersebut bukan masalah ijtihadi, maka para pendukung prinsip ini berargumentasi dengan cara yang sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Bagi mereka yang percaya bahwa setiap mujtahid itu benar, dan terjadi perselisihan pendapat di kalangan mereka sendiri, maka Abu ‘Ali berpegang pada pendapat bahwa ini akan dianggap sebagai ijma’ jika pendapat tersebut tersebar luas dan waktu telah lama berlalu. Abu Hasyim menyatakannya bukan bukan sebagai ijma’, melaikan suatu otorita. Berbeda dengan itu, Abu ‘Abdullah berpendapat bahwa ini bukan ijma’ dan bukan pula otorita.
Penolakan terhadap Ijma’ diam-diam
Dalam persoalan ijma’ sukuti terdapat beberapa pendapat ulama mujtahid yang menolaknya. Apakah persoalan seperti itu dikatakan ijma’ dan mengikat seluruh umat Islam serta bisa dijadikan hujjah?
Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah, Abu bakar al-Baqillani (wafat 403 H, ulama Malikiyah), dan Imam Al-Ghazali (ulama Syafi’iyah) berpendapat bahwa ijma’ sukuti bukan merupakan ijma’, dan tidak dapat dijadikan hujjah.
Al-Amidi, Ibnu al-Hajib dan al-Kharkhi (ahli ushul fiqh Hanafiyah) berpendapat bahwa ijma’ sukuti tidak dapat dijadikan suatu ijma’. Tetapi bisa dijadikan sebuah hujjah, sedangkan kehujjahannya sekarang adalah dzanni (relatif).
Pendapat Imam Syafi’i soal Ijma' Sukuti
Imam syafi’i menyanggah teori ini dengan menyatakan bahwa tidak ada pernyataan atau tindakan yang dapat dinisbatkan kepada seseorang yang berdiam diri. Atas dasar ini juga, beliau menolak ijma’ para ulama. Beliau menyatakan bahwa jika mayoritas para ulama menyuarakan persetujuan mereka terhadap suatu pendapat hukum mengenai suatu masalah tertentu, maka ijma’akan dicapai. Ini dikarenakan dalam praktiknya, sejauh itulah yang dimungkinkan untuk dicapai (karena menyuarakan pendapat dari tiap-tiap ulama sulit dilakukan).
Karena itulah sikap berdiam diri dari para ulama selebihnya dianggap sebagai kesepakatan mereka untuk mencegah masyarakat agar tidak jatuh dalam kesukaran. Lebih jauh, tidak ada buruknya jika kita menganggap penyuaraan persetujuan dari mayoritas ulama mengenai suatu masalah tertentu sebagai ijma’ yang sah, sebab pendapat minoritas termasuk dalam pendapat mayoritas jika mayoritas ulama berdiam diri terdapat mayoritas.
Baca: Pengertian Madzhab Shahabi dan Penerapannya dalam Ushul Fiqih [PDF]
Jika mayoritas ulama berdiam diri terhadap suatu pendapat mengenai suatu persoalan yang diperselisihkan, maka sikap diam mereka akan dianggap sebagai sikap diam dari semua ulama’. Bagitu juga sebaliknya, jika para ulama menyuarakan atas persetujuan mereka akan dianggap sebagai persetujuan mereka, maka persetujuan mereka akan dianggap sebagai persetujuan semua ulama.
Al-Sarakhsi menyanggah argumentasi dari Imam Syafi’i ini. Beliau menyatakan bahwa sikap berdiam diri dari golongan minoritas dianggap sebagai persetujuan mereka. Bukan karena golongan minoritas menjadi lingkup dari golongan mayoritas, tapi karena apabila mereka tidak setuju, tidaklah halal bagi para ulama untuk tetap berdiam diri dalam menanggapi suatu pendapat mengenai suatu masalah. Mereka wajib menyuarakan pendapatnya jika mereka tidak menyetujuinya, dan mengetengahkan pendapat mereka jika mereka punya pendapat.
Masalah yang akan dihadapi menjadi lebih jelas jika satu atau dua orang ulama menyuarakan pendapat mereka, dan akan lebih jelas jika semakin banyak pula yang menyuarakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Oleh sebab itu, sikap diam dari para ulama’, entah mereka termasuk golongan minoritas atau mayoritas, atas suatu pendapat hukum, asalkan pendapat tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat, maka bisa dianggap sebagai tanda kesepakatan mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, pendapat mayoritas tidak berpengaruh dalam kesepakatan diam-diam. Bahkan ketidaksetujuan dari satu orang ulama yang kompeten pun sudah dianggap cukup untuk menghapus persetujuan diam-diam ini.
Pokok utama argumentasi yang mendukung persetujuan diam-diam (sukuti) ini adalah bahwa sikap diam dari para ulama setelah berlalunya waktu yang diperlukan untuk melakukan pertimbangan, menunjukkan persetujuan mereka. Mengapa? Karena secara hukum mereka punya kewajiban untuk menyuarakan jika mereka tidak setuju.
Pendapat Imam Ghozali soal Ijma' Sukuti
Imam Al-Ghazali menolak keabsahan ijma’ sukuti ini. Ia menyatakan bahwa persetujuan diam-diam bukanlah ijma’ dan bukan pula otorita. Persetujuan ini mungkin diperbolehkan jika keadaannya menunjukkan bahwa mereka yang berdiam diri telah menyembunyikan perwujudan mereka. Ia menyatakan bahwa pendapat hukum dari seorang ahli hukum diketahui melalui ungkapan lisannya yang eksplisit, yang tidak bisa diragukan sedikit pun. Tapi sikap berdiam diri adalah meragukan.
Berikut ini adalah kemungkinan alasan seorang ulama’ berdiam diri dalam menanggapi suatu masalah yang sedang diperselisihkan:
- Dimungkinkan ada halangan tersembunyi yang mencegahnya untuk menyuarakan pendapatnya dan hal itu mungkin tidak diketahui oleh para ulama lainnya. Konteks kemarahannya misal, dengan sikap diam, kadang-kadang menunjukkan pendapatnya.
- Ia mungkin menganggap pendapat dari seorang ulama sebagai pendapat yang diperbolehkan menurut penafsiran sendiri (ijtihad), meskipun ia sendiri mungkin berbeda pendapat dengannya dan menganggap pendapatnya sendiri salah.
- Mungkin ia percaya bahwa setiap mujtahid (ahli hukum) adalah benar. Karena itu ia mungkin tidak menganggap perlu menolak pendapat mengenai masalah-masalah yang menyangkut pendapat. Ia mungkin berfikiran bahwa menanggapi masalah secara lisan adalah kewajiban kolektif. Ia mungkin menganggap pendapat dari ulama lain sebagai yang benar, meskipun mungkin bertentangan dengan pemikirannya sendiri.
- Ia mungkin memaksudkan sikap diamnya itu sebagai bentuk penolakan, tapi mungkin ia menunggu waktu yang tepat. Ia mungkin tidak mau tergesa-gesa dalam menyuarakan pendapatnya karena adanya suatu halangan yang dihadapinya, dan ia mungkin pula menunggu sirnanya halangan itu. Mungkin pula ai meninggal atau sibuk dengan persoalan lain sehingga perhatiannya pada masalah yang bersangkutan berkurang.
- Ia mungkin merasa khawatir bahwa jika ia menyuarakannya, pendapatnya akan ditolak, dan ia akan mendapat malu. Ibnu Abbas misalnya menjelaskan tentang sikap diamnya pada masalah ‘awl (kenaikan) dengan mengatakan bahwa ia takut dengan Umar pada masa hidupnya, karena ia adalah orang yang sangat dihormati.
- Ia mungkin memikirkan masalah tersebut sepanjang waktu sementara ia berdiam diri. Masa pemikirannya mungkin diperpanjang.
- Dia mungkin menganggap penolakan diri ulama’-ulama’ lain sudah cukup mewakili dirinya. Tapi mungkin salah alam anggapan ini.
Al Ghazali mengkritik argumen-argumen yang dikemukakan untuk menunjang ijma’ diam-diam oleh para pendukungnya dalam bentuk dialog singkat sebagai berikut:
Para pendukung:
"Jika memang ada keterpaksaan dalam ijma’ sukuti, pastilah hal itu diketahui. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketidaksepakatan dalam hal ini".
Al-Ghozali:
“Argumen yang sama juga dapat dikemukakan terhadap kesepakata. Apa yang mencegah ketidaksepakatan untuk diketahui juga mencegah kesepakatan hingga tidak bisa diketahui. Ini menyanggah pendapat al-Jubba’i yang menetapkan berlalunya waktu sebagai syarat keabsahan ijma’ sukuti. Bisa dicatat bahwa penghalang tersebut mungkin akan tetap ada sampai berakhirnya masa suatu generasi,
"Mereka menganggap kesepakatan yang diam-diam sebagai suatu ketentuan yang mengikat juga tidak benar, sebab kesepakatan semacam itu merupakan pendapat yang asal-asalan saja (arbitrary). infalibilitas (keadaan tidak dapat berbuat kesalahan) ijma’ dalam keadaan yang ditetapkan adanya kesepakatan penuh, bukan melalui pendapat yang asal-asalan".
Para pendukung:
"Adalah kenyataan yang telah masyhur bahwa setiap kali para tabi’in berselisih pendapat mengenai suatu masalah, dan pendapat para sahabat sudah dikenal luas dan disetujui secara diam-diam dilaporkan kepada mereka, maka mereka tidak pernah menyimpang daripadanya. Ini menunjukkan bahwa mereka menyetujui ijma’ sukuti".
Silang Pendapat Ijma' Sukuti
Jika para ulama bersepakat dalam suatu masalah tertentu melalui tindakan-tindakan mereka dan tidak ada seorang pun yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka, keabsahan ijma’ diam-diam semacam ini dipersilakan. Menurut suatu pendapat, ia tetap sah sebagaimana tindakan-tindakan Nabi, karena infalibilitas dari tindakan-tindakan para ulama itu ditetapkan berdasarkan keutamaan kesepakatan mereka, seperti infalibilitas Nabi. Tindakan sepakat mereka sejajar dengan tindakan-tindakan Nabi dalam hal infalibilitasnya.
Pendapat lain mengatakan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui tindakan-tindakan para ulama tidak dapat dianggap sebagai ijma’. Sebab mufakat penuh dari para ulama mengenai suatu masalah tertentu melalui ungkapan lisan atau melalui tindakan-tindakan mereka adalah mustahil. Terutama jika jumlah mereka tidak diketahui.
Pendapat lain ada yang menyatakan bahwa kesepakatan melalui tindakan, adalah mungkin. Tapi dalam hal ini ijma’ akan menunjukkan sifat membolehkan (ibahah) dari suatu tindakan, kecuali jika tindakan itu berdasarkan dalil yang pasti, dibuktikan sebagai bersifat wajib atau dipujikan (sunnah).
Sementara itu, ijma’ tidak bisa ditetapkan melalui tindakan yang dimaksudkan sebagai pengganti artikulasi (bayan) atau ketentuan (al-hukm). Pendapat ini diyakini oleh Ibnu as-Sam’ani. Jika seorang ahli hukum melakukan suatu tindakan dan para ahli hukum lainnya berdiam diri ketika diberi tahu, maka sikap berdiam diri ketika diberi tahu tentangnya, bisa dianggap sebagai ijma’ diam-diam, dengan syarat; generasi di masa peristiwa itu terjadi telah berlalu. Ini pendapat dari Az-Syirozi juga, dengan catatan: jika generasi itu belum berlalu, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahannya.
Pendapat mengenai keabsahan kesepakatan diam-diam bermula sejak masa Imam As-Syafi’i, dimana ia sendiri menolaknya. Pendapat-pendapat yang beragam mengenai masalah ini dinisbatkan kepadanya oleh para ahli hukum Islam klasik. Ijma’ dengan berdiam diri telah ditolak oleh para penentangnya dikarenakan sifatnya yang kurang jelas.
Al-Jashshash dan al-Sarakhsi telah mengatasi masalah perdebatan ini secara lebih mendetail dan berusaha untuk menyanggah argumentasi-argumentasi itu, baik yang pro maupun yang kontra. Al-Amidi pun mengambil jalan tengah; "kesepakatan diam-diam adalah otorita yang sifatnya mungkin, dan argumentasi yang disasarkan atasnya boleh dianggap sah pada lahirnya (dzahir) saja, tapi tidak bisa menentukan (qath’i)". [dutaislam.com/ab]
[Download versi PDF]
Rizal Hizbul Afif, mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
Artikel disampaikan di hadapan dosen pengampu, Mishbah Khoiruddin Zuhri, M.A
DAFTAR PUSTAKA
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmul Ushul, (Maktabah Da’wah Islam, Pdf).
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Muhammad bin Sholeh, Al-Ushul min Ilmil Ushul, (Iskandariyat: Darul iman, 2001)
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
Keyword: contoh ijma | dasar hukum ijma | tingkatan ijma | pembagian ijma | ijma bayani | rukun dan syarat ijma | pertanyaan tentang ijma | ijma sukuti menurut imam syafii | ijma sukuti dalam perdebatan para ulama | ijma sukuti imam ghazali