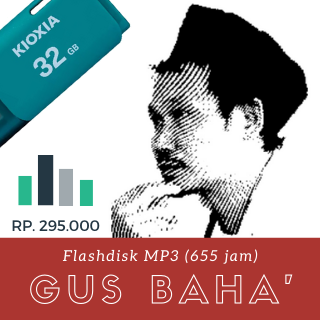|
| Foto: Istimewa |
DutaIslam.Com - Belakangan ini publik, internasional maupun domestik, diramaikan dengan wacana tentang “tata busana” bagi perempuan Arab Saudi. Pasalnya adalah sejumlah kalangan elite, baik elite kerajaan maupun klerik atau sarjana agama, mewacanakan tentang ketidakwajiban bagi perempuan Saudi di ruang publik untuk mengenakan abaya (“jilbab gelombor”) warna hitam dan bahkan “hijab syar’i”, apalagi niqabatau burqa (cadar).
Putra Mahkota Muhammad bin Salman, misalnya, seperti diliput berbagai media dalam dan luar negeri, menyatakan dengan terang-terangan bahwa perempuan harus dibebaskan dalam hal tata-busana (Emirates Woman2018). Menurutnya, sepanjang mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma-norma kepantasan dan etika publik di Saudi, maka hal itu sudah cukup, tidak perlu dan tidak harus memakai abaya, hijab, apalagi cadar. Dengan kata lain, berpakaian bagi perempuan, sebagaimana buat laki-laki, adalah sebuah pilihan masing-masing individu, bukan pemaksaan.
Selama ini, Bin Salman memang dikenal sebagai elite politik berhaluan progresif-moderat yang banyak melakukan terobosan-terobosan penting dan fundamental dalam hal kepolitikan, perekonomian, feminisme, maupun keagamaan dan kebudayaan. Bukan hanya soal busana perempuan saja, Bin Salman juga mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan memiliki SIM sendiri, menonton olahraga di stadium campur dengan laki-laki, serta boleh bekerja di berbagai sektor publik, termasuk di bidang keamanan. Ia juga memprakarsai sektor turisme, pembukaan kembali industri sinema yang sempat lama mati suri dan juga konser musik dengan menampilkan para musisi lokal maupun mancanegara.
Muhammad bin Salman bukan satu-satunya “elite moderat-progresif” di Saudi, khususnya mengenai tata-busana ini. Sebelumnya, Putri Rima binti Bandar Al-Saud, Ketua Saudi Federation for Community Sports (SFCS), di berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa hijab dan abaya, apalagi cadar, bukanlah hal fundamental dan substansial. Yang lebih penting dan harus serius diperhatikan adalah tentang kemampuan dan kualitas perempuan itu sendiri, bukan tetek-bengek soal pakaian (Arab News 2018). Putri Rima sendiri selalu mengenakan pakaian kasual warna-warni dengan kerudung biasa, bukan abaya dan hijab hitam, apalagi cadar.
Bukan hanya kalangan elite politik dan keluarga kerajaan saja, sejumlah elite agama dan ulama senior juga mengemukakan hal serupa. Misalnya Syaikh Abdullah Al-Mutlaq, anggota Council of Senior Scholars, menyatakan dan menegaskan bahwa perempuan tidak harus memakai abaya di ruang publik. Baginya, perempuan cukup berpakaian yang sopan dan pantas. Syaikh Abdullah juga menyatakan lebih dari 90% perempuan Muslimah di dunia ini juga tidak memakai abaya (Saudi Gazette 2018).
Pro-Kontra Reaksi Publik
Seperti biasa, publik menanggapi beragam tentang “reformasi busana” kaum perempuan di Saudi ini. Ada yang menyambut optimis, positif dan riang-gembira. Ada pula yang menyambutnya dengan pesimisme dan penuh kekhawatiran. Sejumlah pengamat juga mewanti-wanti atau memberi peringatan kalau “reformasi radikal” ini bisa berbuntut pada pemberontakan kelompok militan agama dan kalangan konservatif.
Sebetulnya jika mengamati dengan seksama pernyataan Bin Salman, Putri Rima maupun Syaikh Abdullah itu bukanlah datang secara tiba-tiba dan tidak memiliki landasan sosial-faktual di masyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak mendiang Raja Abdullah yang dikenal sebagai “raja moderat-progresif”, gaya berbusana kaum perempuan Saudi memang cukup longgar. Keliru besar anggapan yang menyatakan bahwa semua perempuan Saudi mengenakan abaya, hijab, dan cadar hitam ala ninja.
Dalam perkembangan terakhir ini, warnaabaya warna-warni tidak melulu hitam dan bahkan penuh dengan pernak-pernik bordir. Banyak gerai atau toko busana maupun mal yang memajang aneka jenis busana abaya ini. Bahkan ada anggapan bahwa “abaya hitam” tanpa bordir itu sudah “kuno” karena tidak modis dan stylish. Perempuan mengenakan abaya warna-warni sudah menjadi pemandangan biasa di Saudi.
Dalam konteks Saudi, abaya bukan sekadar pakaian penutup tubuh atau penanda moralitas perempuan, tetapi juga menunjukkan “kelas sosial” yang memakainya. Jadi, perempuan yang mengenakan abaya dengan desain keren dan warna-warni dipersepsikan sebagai “kelas menengah-atas”, bukan “kelas bawah” (misalnya pekerja sektor domestik rumah tangga) yang biasanya mengenakan abaya hitam dengan desain sederhana dan minimalis.
Ada semacam “hukum tak tertulis” yang menyatakan bahwa “abayamu adalah dirimu”. Di kalangan kaum perempuan Indonesia di Saudi, ada gurauan kalau tidak ingin dianggap sebagai “pembantu rumah tangga”, maka jangan mengenakan abaya hitam sederhana kalau di tempat umum tapi pakailah abaya yang modis dan warna-warni.
Perempuan Saudi sendiri sebetulnya sudah lama merindukan kelonggaran berbusana. Selama ini mereka mengenakan pakaian “superbrukut” (serba tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki) di ruang-ruang publik di Saudi bukan karena kesadaran pribadi atau dalam rangka mengikuti anjuran dan perintah ajaran/doktrin agama, tetapi lebih karena ketakutan terhadap hukuman pemerintah maupun kelompok militan agama (kaum Wahabi ultrakonservatif, khususnya “polisi syariat”) yang mendominasi dunia kepolitikan dan wacana keagamaan terutama sejak akhir 1970an, pascaserangan terorisme ekstremis Juhaiman al-Otaibi.
Maka, ketika otoritas “polisi syariat” dipreteli dan tidak lagi berpengaruh dan memiliki kekuasaan mutlak untuk menghakimi, pelan tapi pasti kelonggaran berbusana menyapa kaum perempuan Saudi.
Bukti nyata bahwa berpakaian brukut itu lebih karena “strategi budaya” untuk menghindari hukuman (legal and religious punishment) bisa dilihat pada saat kaum perempuan bepergian keluar Saudi ketika, pada umumnya, mereka mengenakan busana kasual-praktikal, kecuali kelompok emak-emak berusia lanjut yang tetap berabaya gelombor.
Fenomena ini juga dikisahkan oleh murid-murid Saudiku. Misalnya Muhammad al-Zaini pernah mengungkapkan ketika dia dan keluarga besarnya bepergian atau liburan ke Dubai dan kota-kota lain sering atau bahkan selalu tidak mengenakan abaya bagi saudara-saudara perempuannya.
Lebih dari itu, di kompleks-kompleks perumahan (compound) seperti di Aramco dan di kompleks perumahan kampus tempat saya mengajar saat ini, perempuan dengan busana yang lebih fleksibel merupakan pemandangan yang lumrah dijumpai sehari-hari. Bahkan ada kesan para perempuan dari Pakistan atau India tampak lebih konservatif dalam berbusana ketimbang warga Saudi atau Arab non-Saudi atau perempuan non-Arab/Pakistan/India (misalnya dari kawasan Asia, Afrika atau Eropa).
Cermin Perubahan Sosial dan Strategi Bin Salman
Jadi, apa yang dikemukakan Bin Salman di atas sebetulnya merupakan cerminan, refleksi, atau respons atas perubahan sosial-budaya yang sudah terjadi di Saudi sejak beberapa tahun terakhir ini. Dengan kata lain, Bin Salman hanya “mengechokan” atau menggemakan apa yang terjadi di masyarakat. Dia menyadari dan bisa membaca situasi dengan baik bahwa aroma aksi yang menuntut perubahan fundamental hal-ihwal yang berkaitan dengan masalah perempuan itu cukup bergema di masyarakat, khususnya masyarakat urban.
Gaung emansipasi perempuan dan pemikiran tentang pentingnya pemerintah untuk fokus pada kualitas dan kapabilitas ketimbang busana perempuan itu juga digelorakan oleh para elite dan sarjana perempuan yang duduk di Dewan Penasehat Kerajaan (Shuro Council). Sejak Raja Abdullah, perempuan menempati kuota 30% di Shuro Council. Mereka inilah yang selama ini banyak melakukan dan menyuarakan perubahan atas hak-hak kaum Hawa di Saudi.
Muhammad bin Salman menyadari bahwa kaum muda-mudi adalah tulang punggung (backbone) bagi masa depan Arab Saudi karena mereka menempati mayoritas dari populasi penduduk. Kebijakan dramatis Bin Salman juga dimaksudkan untuk mendorong agar kaum muda-mudi yang studi di luar negeri, khususnya di Amerika Utara dan Eropa Barat, kembali ke Saudi.
Sejak Raja Abdullah, ada ratusan ribu kaum muda-mudi yang belajar di luar negeri dengan dibiayai oleh kerajaan lewat King Abdullah Scholarship Program (itu belum termasuk beasiswa yang dikeluarkan oleh donor individu maupun kalangan swasta seperti Aramco, SABIC, dan seterusnya). Setelah selesai kuliah, ternyata banyak dari mereka yang enggan pulang ke negerinya karena faktor konservatisme kultural-agama di Saudi. Maka, dengan berbagai reformasi substansial di bidang sosial-budaya ini diharapkan mampu mendorong dan merangsang mereka untuk kembali ke Saudi dan turut berpartisipasi membangun negara mereka di kemudian hari.
Apakah kebijakan progresif Bin Salman akan mendapat perlawanan dari kelompok militan dan ultrakonservatif? Perlawanan sudah pasti ada tetapi di mana-mana kelompok militan dan ultrakonservatif itu tidak pernah menjadi mayoritas. Di Saudi pun sebetulnya kaum Wahabi militan dan ultrakonservatif itu sangat minor dan marjinal. Mayoritas warga Saudi adalah kaum pragmatis-ekonomis, bukan radikal-militan.
Jadi, sepanjang perubahan-perubahan sosial-budaya itu tidak mengganggu kebutuhan dasar finansial dan kesejahteraan ekonomi keluarga (misalnya uang lancar, pendidikan gratis, kesehatan terjamin, sewa rumah murah, harga-harga makanan dan bahan-bahan pokok tidak melonjak dan sebagainya), semua akan berlangsung baik-baik saja. Faktor pragmatisme masyarakat inilah sebabnya kenapa fenomena “Arab Spring” tidak mampu menjamah Saudi. [dutaislam.com/pin]
source: Geotimes