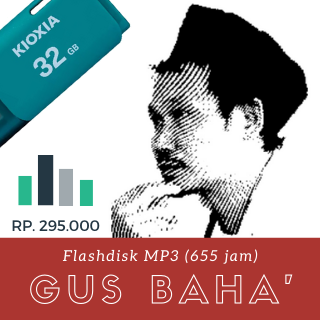|
| Foto: Nu Online |
Hijrah ala kelompok islam dari bacaan “ terjemahan” itu hanya bicara bungkus. “Hijrah ya dari sarung ke cingkrang atau dari krung ke cadar” kira-kira begitu istilahnya. Ketahuan kalau tak paham sejarah. Salah sendiri sih, bacanya terjemahan.
Mau tahu makna hijrah yang benar ? Yuk, ngintip tulisannya Muhammad Afiq Zahara* berikut ini:
Hijrah: Sebuah Renungan
Imam al-Ghazali (1058-1111 M) dalam pendahuluan Tahâfut al-Falâsifah(Inkoherensi Para Filosof) mengutip perkataan Aristoteles (384-322 SM): “Aflathon shadîq wa al-haq shadîq, wa lakin al-haq ashdaqu minhu—Plato sangat berharga, kebenaran pun sangat berharga, tapi kebenaran jauh lebih berharga dari Plato.” (Abû Hâmid al-Ghazali, Tahâful al-Falâsifah, Kairo: Darul Ma’arif, 1972, hlm 76).
Sepanjang tahun pernahkan kita mengingat dosa-dosa kita, menyesalinya dan bersungguh-sungguh memohon ampunanNya? Sepanjang tahun pernahkan kita menyadari kenikmatan hidup kita, mensyukurinya dan berserah diri kepadaNya? Kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri, apakah kehadiran Sang Nabi yang membawa cahaya—min al-dhulumât ilâ al-nûr—benar-benar telah merubah diri kita yang dipenuhi kegelapan menjadi bercahaya. Jika belum, inilah saatnya, hijrah.
Dalam Islam, ada dua jenis hijrah: pertama, hijrah zahir (fisik), yaitu berpindah tempat tinggal, dan kedua, hijrah jiwa (spiritual), yaitu berpindahnya keadaan jiwa ke arah yang lebih baik. Mengenai hijrah jiwa (spiritual) yang menuju pada perbaikan diri, Rasulullah bersabda (H.R. Imam Bukhari): “Al-Muhâjir man hajara mâ naha Allahu ‘anhu—muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan segala laranganNya.”
Dari sudut pandang fisik, hijrah yang dilakukan Rasulullah Saw adalah sebuah transisi di antara dua situasi, dari keadaan yang tidak aman dan lemah (Mekkah) menuju keadaan yang aman dan kuat (Madinah). Sedangkan dari sudut pandang spiritual, hijrah dipahami sebagai transisi dari keadaan lemah manusia atas dosa menjadi keadaan yang kuat dan terus berjuang untuk menghindarinya. Keadaan yang penuh dengan kelalaian menuju kesadaran spiritual yang sehat.
Proses pengembangan jiwa pun terus berlangsung, tidak berhenti sampai di situ. Sebagaimana kata Aristoteles di atas, meski Plato sangat berharga baginya, Ia tidak berhenti dan terus melakukan pencarian kebenaran. Katanya:“Kebenaran jauh lebih berharga dari Plato.” Bukan berarti Aristoteles tidak menghormati Plato, tapi baginya kebenaran masih terlampau luas untuk digali, dan Plato belum menggali semua kebenaran itu, sekedar buih dalam lautan jika dibandingkan.
Tidak berbeda dengan keadaan jiwa (state of soul). Dalam literatur tasawuf, ada istilah yang disebut dzunûb al-ahwâl (dosa keadaan jiwa). Menurut Syeikh Musthafa al-‘Arûsi (1798-1876 M) penyebab dosa keadaan jiwa adalah sifat-sifat buruk (madzmûm al-shifât) yang menyamarkan manusia dalam kebaikan, yaitu al-wuqûf ma’a istihsânihâ—berpuas diri dengan anggapan bahwa dirinya berada dalam kebaikan (Musthafa al-‘Arusi, Natâ’ij al-Afkar, Beirut: Darul Kutub, al-Ilmiyyah, 1971, juz 2, hlm 169).
Dengan kata lain, mencukupkan diri dengan tidak melakukan observasi terhadap jiwanya, karena telah meyakini bahwa dirinya berada dalam kebenaran. Anggapan baik inilah yang membuat manusia berhenti untuk memperbaiki kualitas ibadahnya.
Maka dari itu,setiap hari atau minimal satu tahun sekali, kita harus memeriksa diri kita, melakukan observasi dan analisis diri, ‘Apakah kita masih sering lalai? Seberapa banyak dosa kecil yang kita perbuat? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Tuhan? Seberapa banyak amal ibadah kita? Kenapa kita berhenti pada pencitraan baik ibadah kita? Kenapa kita tidak meningkatkan kualitasnya? Kenapa kita merasa cukup dengan kebaikan kita? Padahal, kebaikan tidak akan pernah habis diamalkan dan direnungkan.’
Benar, kita harus terus berproses menuju pada kebaikan, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Kita tidak boleh puas dengan ibadah kita. Kita harus selalu meningkatkannya; dari menyembah karena takut siksaNya berubah menjadi cinta akan ridlaNya; dari menyembah karena mengharapkan pahalaNya berubah menjadi cinta akan diriNya.Wajar saja, apabila para ulama kita terdahulu karena keinginannya untuk terus meningkatkan kualitas ibadahnya, berdoa dengan cara yang unik. Imam Hârits bin Asad al-Muhâsibi (781-857 M) berkata:
Artinya:
“Tidak pernah aku mengatakan: “Ya Allah aku memohon taubat kepada-Mu,” sebaliknya aku mengatakan: “(Ya Allah) aku memohon syahwat taubat kepada-Mu.” (Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi, Risâlah al-Qusyairiyyah, hlm 183).
Dengan memohon syahwat dalam doanya, Ia tidak akan berhenti mengaktualisasikan dirinya. Taubatnya adalah perjalanan panjang laiknya hijrah yang dilakukan Nabi Saw dan para sahabatnya. Perjalanan menuju ke arah yang lebih baik setiap waktunya. Syahwat itulah yang membuat Imam Hârits al-Muhâsibi terus bernafsu mencintaiNya dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Shalatnya sekarang, berbeda pengalaman spiritualnya dengan shalatnya kemarin. Zikirnya besok, berbeda rasa spiritualnya dengan zikirnya sekarang.
Bagaimana dengan kita? Telah berapa kali kita mendengar adzan? Telah berapa kali kita bertemu dengan tahun baru Hijriah? Apakah kita pernah merenungkannya sejenak? Mengambil maknanya yang luhur? Dan, memperbaiki diri setiap kali melaluinya?
Ibadah kita masih sekedar takut akan siksaNya dan menginginkan surgaNya. Karenanya, kita disibukkan dengan meningkatkan kuantitasnya, bukan kualitasnya. Shalat yang seharusnya tanhâ ‘an al-fakhsya’ wa al-munkar (mencegah perbuatan keji dan munkar) tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak orang shalat, tapi masih berbuat jahat; korupsi, menggunjing, menghina, memfitnah dan seterusnya. Ibadah kita seakan pakaian baru di hari raya, tapi tidak membarukan jiwa kita.
Ketika melaksanakan shalat, kita tidak merasa bahwa kita sedang menyembahNya. Kita terjebak pada lingkaran rutinitas, aktifitas sehari-hari. Shalat telah menjadi kebiasaan hidup yang kering spiritualitas.Kita lalai untuk siapa shalat kita, hidup kita, mati kita dan ibadah kita.Kita perlu melihat kepada diri kita dan berhijrah dari kekeringan spiritual menuju kesuburan spiritual. Bukan berarti ibadah kita tidak ada nilai pahalanya, tidak. Namun, alangkah baiknya jika pahala itu bersanding lurus dengan perubahan diri yang baik.
Kita selalu menuntut Tuhan ketika semuanya tidak berjalan dengan baik. Kita merasa telah melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Lalu, ‘kenapa Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita?’ Kita, dengan tanpa sadar, menggunakan persepsi bahwa ibadah seperti tabungan di bank, bisa diambil ketika kita membutuhkan. Karena itu, setiap kali ada masalah, kita akan menuntut Tuhan: “aku telah menjalankan perintahMu dan menjauhi laranganMu, kenapa Kau mengujiku dengan masalah seperti ini?”
Kita menggunakan teori kausalitas (sebab-akibat) dalam hubungan kita dengan Tuhan, take and give, harus saling menguntungkan. Kita tidak sadar bahwa Tuhan tidak butuh keuntungan dari kita. Segala perintah dan laranganNya adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan rugi jika semua manusia tidak menyembahNya.
Karena itu, dalam momen penuh berkah ini, tahun baru Hijriah 1439, kita harus merenung dalam diam, menerawang ke dalam diri, membiaskan hikmah agungnya, kemudian melakukan intropeksi diri (muhâsabah). Kita pun harus melakukan penataan ulang kualitas-substantif ibadah-ibadah kita. Soren Kierkegaard (1813-1855 M) mengatakan: “Prayer does not change God, but it changes him who prays—ibadah tidak merubah Tuhan, tapi merubah manusia yang melakukannya.”
“Tujuanku bukan surga yang dipenuhi kenikmatan.Sungguh, aku menginginkannya, bukan karena nikmat surgawinya, tetapi karena aku ingin berjumpa denganMu”
(Sa’id Harun ‘Asyur, Jawâhir al-Tashawwuf li al-‘Arif bi Allah al-Zâbid al-Wâ’idh Yahya bin Mu’âdz al-Razi, Iskandariyyah: Maktabah al-Adab, 2002, hlm 31) [dutaislam.com/pin]
Penulis adalah Alumnus Pondok Pesantren al-Islah, Kaliketing, Doro, Pekalongan dan Pondok Pesantren Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen.