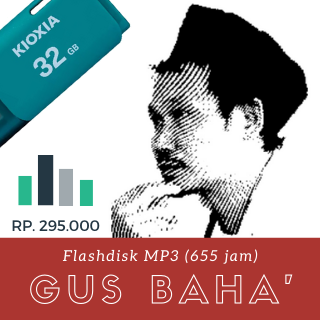Oleh Muhammad Makmun-Abha
DutaIslam.Com - Dalam beberapa dekade terakhir hingga hari ini, Indonesia dan dunia Islam sedang digoyang “bola panas” atas bergulirnya wacana mengusung kembali sistem khilafah oleh sebagian kelompok kecil (baca: minoritas) dalam Islam, khususnya dari kelompok hizb al-tahrir maupun kelompok muslim lain yang sejenis dengannya.
Hal ini justru tampak sangat ironis mengingat tidak semua ‘ulama, pemikir dan cendikiawan muslim –dalam lintasan sejarah- sependapat bahwa Islam datang dengan ajaran agama dan juga dengan sistem bernegara sekaligus. Imam Al-Syihristani misalnya dalam magnum opusnya al-Milal wa al-Nihal menyatakan bahwa di antara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. adalah masalah imamah. Persoalan imamah diperdebatkan kala itu karena tidak ada teks al-Qur’an maupun Sunnah yang “tegas” (baca: sharih) menjelaskan bentuk pemerintahan dalam Islam.
Senada dengan Al-Syihristani, Khalil Abd al-Karim, seorang pemikir asal Mesir juga menyatakan bahwa hakikat dari apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW di Madinah adalah manifestasi dari Islam sebagai daulat diniyyat bukan daulat siyasiyyat. Argumen yang dijadikan dasar Khalil Abd al-Karim adalah andaikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah terdapat aturan baku tentang bentuk formal dan sistem pemerintahan dan pergantian kekuasaan dalam Islam, maka tidak mungkin para sahabat berdebat dan berijtihad untuk mengangkat pengganti Rasul yang selanjutnya disebut sebagai khalifah dalam sistem khilafah.
Argumen ini logis karena para sahabat adalah orang yang lebih paham atas Al-Qur’an dan Sunnah, karena di hadapan dan di sekitar merekalah Al-Qur’an dan Sunnah muncul. Namun yang terjadi justru para sahabat berdebat bahkan masing-masing sahabat Anshar dan Muhajirin sama-sama berminat untuk menjagokan tokoh masing-masing meskipun akhirnya disepakati dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam rundingan di Saqifah Bani Sa’idah.
Khilafah dan politik Islam sebagai Produk Ijtihad
Perlu dicatat, ketika Nabi Muhammad SAW membangun komunitas baru di Madinah, beliau tidak pernah mengemukakan satu pun bentuk pemerintahan politik yang baku dan harus diikuti oleh para penerusnya. Nabi hanya memberikan inspirasi dan contoh garis besar akan nilai-nilai terbaik yang harus ada dalam sebuah pemerintahan yang Islami.
Apa yang disebut sebagai politik Islam sebenarnya tidak lebih hanyalah bentuk dari “ijtihad politik” para elit muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa tidak ada mekanisme politik standar dan baku yang berlaku bagi pergantian pemerintahan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan ironisnya di antara ke empat sahabat besar ini hanya Abu bakar lah yang meninggal dengan cara yang yang wajar, karena yang lain (Umar, Utsman, dan Ali) meninggal dengan cara terbunuh.
Meski demikian, khilafah rasyidiyyah ini merupakan contoh sistem khilafah terbaik yang pernah ada dalam sejarah khilafah Islamiyyah dengan sistem demokrasi dalam menentukan seorang khalifah. Hal ini tentu berbeda jauh bila dibandingkan dengan khilafah model dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan seterusnya yang terkesan jauh dari spirit Islami yang menjunjung tinggi nilai demokrasi di mana pergantian pemerintahan ditentukan berdasarkan sistem monarkhi absolut.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem khilafah atau yang disebut dengan imamah dalam terminologi sekte Syi’ah tidak lebih dari sekedar hasil ijtihad yang cocok diterapkan pada masanya dan belum tentu sesuai di era masa kini.
Di antara pemikir yang berpandangan demikian adalah Ali Abd al-Raziq, seorang ilmuan dari Mesir, Ia menjelaskan bahwa al-Qur’an menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan sebagai sarana esensial bagi umat Islam dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya.
Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok Islam. Ini jelas menunjukkan bahwa Ali menerima keberadaan otoritas politik dalam umat Islam. Meski begitu, ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntutan syari’ah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan.
Prinsip Umum Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an
Terlalu berlebihan jika dikatakan Islam mengatur bentuk baku suatu pemerintahan, akan tetapi di waktu yang bersamaan juga tidak bijaksana untuk mengatakan bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik.
Pendapat yang moderat mengatakan bahwa kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat beberapa nilai atau ide tentang bentuk kekuasaan politik (pemerintahan) yang ideal, meskipun Islam tidak berbicara langsung mengenai bentuk negara tertentu yang diakui. Sehingga pemerintahan Islami bukanlah pemerintahan dalam negara Islam melainkan pemerintahan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang diusung oleh Islam.
Di antara nilai-nilai ideal yang harus melekat dalam pemerintahan Islami yaitu: pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan. Islam mengajarkan bahwa semua rakyat memiliki persamaan hak di hadapan undang-undang dan hukum tanpa memandang adanya keistimewaan hak dan kedudukan atau perbedaan warna kulit, suku, bahasa atau tanah air.
Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. al-Nisa’: 58)
Kedua, menujunjung tinggi prinsip demokrasi atau yang sering disebut dengan musyawarah-syura. Prinsip ini merupakan prasyarat mutlak dalam menunaikan amanat kepada yang berhak dan berbuat adil kepada semua masyarakat. Pemimpin negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyat yang dipimpinnya dalam mengambil kebijakan bagi negara. Di sini akan muncul pertanyaan, hal apakah yang dapat dimusyawarahkan? Apakah urusan dunia semata atau juga urusan agama?
Menurut Rasyid Ridha, materi yang dimusyawarahkan hanyalah yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Namun pendapat Rasyid Ridha ini tidak sejalan dengan para pendahulunya, semisal al-Thabari, al-Razi dan Muhammad Abduh. Bagi mereka, urusan yang dimusyawarahkan bukan hanya urusan keduniaan tapi juga urusan keagamaan. Dengan begitu pendapat ini memandang jauh bahwa musyawarah tidaklah kaku dan terbatas dalam bentuk dan objek tertentu melainkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi sehingga tidak menyulitkan umat Islam.
Ketiga, prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar. Setiap individu dalam negara Islami memiliki hak, bahkan kewajiban untuk mengatakan sesuatu yang benar, menyerukan yang ma’ruf, membela kebaikan dan mempertahankannya, serta di waktu yang bersamaan berupaya sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum setiap bentuk kebatilan.
Negara yang ideal adalah yang mampu menegakkan perintah agama, tetapi eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukan lembaga keagamaan itu sendiri. Sehingga untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar tidak perlu dalam bentuk khilafah tetapi dalam bentuk apapun itu, yang terpenting adalah berjalannya prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar.
Bahkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah pernah berkata, “Tuhan akan melanggengkan suatu negara yang menjaga prinsip keadilan, walaupun negara tersebut, secara formal, bukan negara Islam. Akan tetapi, sebaliknya, Tuhan akan menghancurkannya apabila nilai-nilai tersebut dikesampingkan meskipun scara formal merupakan Negara Islam”.
Menolak Sistem Khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sehubungan dengan amat sulitnya implementasi khilafah di masa kini bila dikembalikan seperti model khilafah masa silam, maka perlu adanya konseptualisasi kembali termimologi khilafah model baru sebagai alternatif dalam memelihara tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syari’ah) dan umatnya. Konseptualisasi ini dikembalikan kepada tujuan pokok Syariah Islam, yaitu jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid.
Maka di sini yang masuk kategori mashlahah ‘ammah, yaitu hifz al-ummah wa hifz al-syarî’ah, wa hifz al-bilād harus dikedepankan daripada konflik horizontal dan vertikal yang mungkin akan timbul di antara umat dengan dipaksakannya model khilafah.
Dengan demikian, memelihara dan menegakkan nilai-nilai Islam (bukan formalism Islam) di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada sekedar menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu bentuk negara yang disebut khilafah. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa model atau bentuk negara adalah persoalan ijtihādî yang sangat mungkin berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain dan antara generasi satu dan generai yang lainnya.
Dengan melihat fakta sejarah seperti di atas, maka umat Islam perlu mengkaji kembali berbagai pandangan tentang khilafah dilihat dari aspek-aspek ta’abbudi atau ta’aqquli-nya. Penulis melihat bahwa khilafah bukan termasuk ta’abbudi, tetapi ia masuk kategori ta’aqquli yang di sana ada ruang untuk munculnya ijtihad di setiap generasi sesuai dengan peluang dan tantangan masing-masing era.
Ciri yang membedakan suatu negara itu Islami atau bukan tidaklah terletak pada sistem khilafah atau sistem lainnya, melainkan dalam implementasi nilai-nilai ketuhanan (tahqiq al qiyam ilahiyah) yang wajib dipelihara, yaitu negara yang berasas tauhid (bukan atheis), dengan menegakkan semua prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu meletakkan manusia sebagai umat yang egaliter dan sepadan di hadapan undang-undang, menegakkan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi nilai demokrasi, amanah, persatuan dan persaudaraan, hidup bertetangga, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, perdamaian, membangun ekonomi yang menyejahterakan, membela tanah air, amar makruf-nahi munkar dan bertanggung jawab.
Dengan begitu, maka suatu pemerintahan (negara) apapun bentuknya, baik republik, kerajaan, kesultanan dan lainnya adalah boleh selama di sana syari’at ditegakkan dan aturan Islam berjalan. Peradaban Islam dan tegaknya syariat, bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Dengan demikian, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945 ini menjadi tanggung jawab Umat Islam Indonesia untuk memajukan, mengurus dan memeliharanya. Negara Kita adalah rumah kita juga. Umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia, sehingga mereka amat berhak membangun negara berdasarkan nilai-nilai yang dianut mayoritas tersebut.
Negara, sebagaimana halnya rumah, harus dibersihkan, dipelihara, dibangun dan dimakmurkan. Hal inilah yang berkali-kali disinggung oleh mantan Rais ’Am PBNU, Dr. (Hc.) KH. Ahmad Mustofa Bisri bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang bergama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia.
Indonesia patut kita warnai dengan nilai-nilai ke-Islam-an yang sesuai dengan kultur masyarakatnya bukan dengan kultur impor yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar menjadi bangsa ini ke depan semakin baik dan menjadi prototype dunia Islam yang mampu menjunjung tinggi nilai toleransi dari waktu ke waktu. Semoga. [dutaislam.com/ab]
Muhammad Makmun-Abha, Intelektual Muda NU,
Alumni PP Darut Ta'lim Jepara dan PP Al Munawwir Krapyak