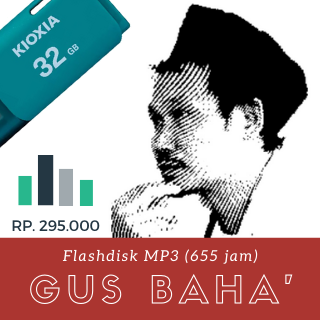Oleh Syaiful Arif
 |
| Syaiful Arif |
Dalam rangka Haul ke-6 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sejak wafat pada 30 Desember 2009, kita perlu mengenang kembali pemikiran dan perjuangannya terutama dalam merawat keindonesiaan. Dalam konteks ini, Gus Dur telah meletakkan rumusan teologi keindonesiaan yang menempatkan Islam, kemanusiaan dan kemodernan secara mutualis.
Rumusan yang membuahkan "negara Muslim demokratis" ini akhirnya tak hanya menjadi model bagi negara Barat sekular, melainkan masyarakat Timur-Tengah yang sampai kini masih belum menemukan bentuk pas Negara Islam.
Disebut teologi karena Gus Dur berangkat dari kesatuan tauhid (teologi), syariah (hukum) dan akhlak (etika) dalam memahami Islam. Artinya, menjadi Muslim ialah menjadi pribadi yang mengimani Keesaan Tuhan yang diamalkan melalui ketaatan terhadap syariah dalam bentuk akhlak yang mulia. Jadi, pijakannya adalah tauhid. Dan meskipun melalui syariah, ibadah seorang Muslim harus mewujud dalam etika. Bukan semata legalisme hukum.
Ini yang membedakan Gus Dur dengan Muslim radikal. Abul A'la al-Maududi, tokoh fundamentalis Pakistan, memiliki rumusan hampir sama. Menurutnya, Islam dibangun oleh tiga pilar; tauhid, syariah dan khilafah. Artinya, ujung dari kepatuhan terhadap Keesaan Tuhan adalah penegakan khilafah yang menaungi pelaksanaan syariah. Ini yang berbeda dengan Gus Dur yang menempatkan etika sebagai praksis dari syariah. Hal ini tak mengejutkan mengingat tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) memang bersifat etis, yakni pememuhan hak asasi manusia.
Menariknya, Gus Dur tak pernah memahami akhlak secara individual. Ia menggagas suatu etika sosial Islam. Ini berangkat dari dua hal. Pertama, dimensi ibadah dalam Rukun Islam bersifat sosial. Misalnya puasa, zakat dan haji yang menandai kepekaan dan kesetaraan sosial. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya bersifat ritus personal melainkan selalu dalam konteks perbaikan masyarakat. Kedua, firman Tuhan dalam al-Baqarah: 177 yang menempatkan kepedulian kepada fakir miskin sebagai penyempurnaan iman.
Dengan demikian, daripada berhasrat menegakkan Negara Tuhan (hakimiyatullah) berbasis syariah, Gus Dur lebih konsen dengan pertanyaan, "Sejauhmana negara mewujudkan tujuan pendiriannya, yakni kesejahteraan rakyat?" Pertanyaan ini merupakan pergeseran paradigmatis dari kecenderungan legalistik dalam memahami negara, kepada pemahaman demokratis, di mana negara dihadirkan demi memenuhi hak-hak dasar manusia.
Selain mendapat asupan pandangan modern, pemikiran demokratik ini juga digalinya dari tradisi Islam. Misalnya, pandangan al-Ghazali yang menempatkan pemenuhan hak warga yang terlindungi (daf'u dlaruri ma'shumin) sebagai kewajiban pemimpin. Hal ini juga ditegaskan oleh kaidah fikih, tasharruful imam 'ala ra'iyyatihi manuthun bil mashlahah (keabsahan kebijakan pemimpin merujuk pada kesejahteraan rakyat). Lokus kebijakan negara dari hukum Tuhan, kepada manusia ini ia dasarkan pada sifat dasar Islam yang humanistik, di mana Tuhan menunjuk manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (Q.S. 2:30) untuk memuliakan umat manusia sendiri (Q.S. 17:70).
Nilai Indonesia
Pandangan politik Islam yang humanistik demokratis ini ia benamkan dalam nilai keindonesiaan yang dirumuskan sebagai, "Perubahan sosial terus-menerus tanpa kehilangan akar tradisi" (Wahid, 1984:8).
Dari nilai ini terdapat dua makna dan konsekuensi. Pertama, perubahan sosial terus-menerus melalui demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan. Ini adalah prinsip utama demokrasi Gus Dur yang merujuk pada demokrasi politik (pemenuhan hak-hak sipil dan politik) demi demokrasi sosial (pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi).
Faktanya Gus Dur tidak hanya berpikir tetapi bergerak. Melalui pendirian Forum Demokrasi (Fordem) di awal tahun 1990-an, ia membentuk blok historis (historical block) bersama aktivis lintas ideologi untuk mengimbangi hegemoni negara. Ia mengritik praktik "demokrasi seolah-olah" Orde Baru, dan menawarkan demokratisasi politik demi tegaknya kebebasan dan penghormatan atas HAM. Ketika menjabat Presiden ke-4 RI, ia juga "mendemokratikkan negara" melalui pengembalian TNI ke baraknya, penegakan supremasi sipil, penghapusan Litsus dan Departemen Penerangan demi berkembangnya kebebasan berserikat dan pers.
Kedua, pemijakan pada akar tradisi dan sejarah. Tentu kita tak asing dengan gagasannya, pribumisasi Islam. Gagasan ini menegaskan bahwa Islam dan semua agama yang hadir di Nusantara telah mengalami pribumisasi budaya. Dengan cara ini, Islam di Indonesia lebih menampakkan bentuknya yang bersifat kultural daripada doktrinal-institusional.
Dari sini lahirlah corak budaya yang kini disebut Islam Nusantara yang ditandai oleh beberapa ciri; (1) akomodasi adat oleh hukum Islam (al-'adah al-muhakkamah), (2) tasawuf sebagai ajaran utama yang didakwahkan, (3) penggunaan kesenian lokal sebagai media dakwah, (4) akulturasi Masjid dengan arsitektur lokal, (5) dan pendirian kerajaan Islam untuk menaungi pelaksanaan syariah.
Menariknya, keberadaan historis kerajaan-kerajaan Islam inilah yang dijadikan legitimasi oleh para kiai pada Muktamar ke-11 Nahdlatul Ulama (NU) di Banjarmasin (1936) untuk mengakui Nusantara sebagai wilayah Islam (dar al-Islam). Dengan fakta ini, Indonesia tidak membutuhkan pendirian Negara Islam (dawlah Islamiyah), karena secara sosiologis sudah Islami. Dengan demikian, Islam yang dipribumisasikan telah menjadi jembatan kultural antara kebudayaan Nusantara dengan kebangsaan modern Indonesia, karena keislaman ini mendukung nasionalisme daripada sektarianisme.
Kontekstualisasi
Lalu bagaimana kontekstualisasi teologi Gus Dur ini di ranah kekinian? Secara politik, ia menginspirasi perlunya pendalaman demokrasi (deepening democracy) agar sesuai dengan prinsip demokrasi di atas. Dalam hal ini, kecenderungan "demokrasi seolah-olah" yang dilihat Gus Dur di era Orde Baru, juga terjadi kini. Bedanya, jika di masa Orba, institusionalisme kenegaraan otoriter telah melibas kualitas substantif demokrasi. Maka di era kini, praktik koruptif berbasis partai dan prosedur demokrasi telah membajak tujuan demokrasi itu sendiri. Dibutuhkan redemokratisasi politik demi tegaknya keadilan sosial.
Pada ranah kultur, menguatnya palingan konservatif (conservative turn) dari kelompok radikal telah menciderai Islam keindonesiaan yang dibangun Gus Dur dan kalangan moderat. Diperlukan penguatan moderatisme Islam demi mengimbangi konservatisisme ini. Pada titik ini, pemikiran keislaman Gus Dur bisa memandu moderasi keislaman di Indonesia demi deradikalisasi agama. [ab]
Source: Suara Pembaruan, 22/12/2015